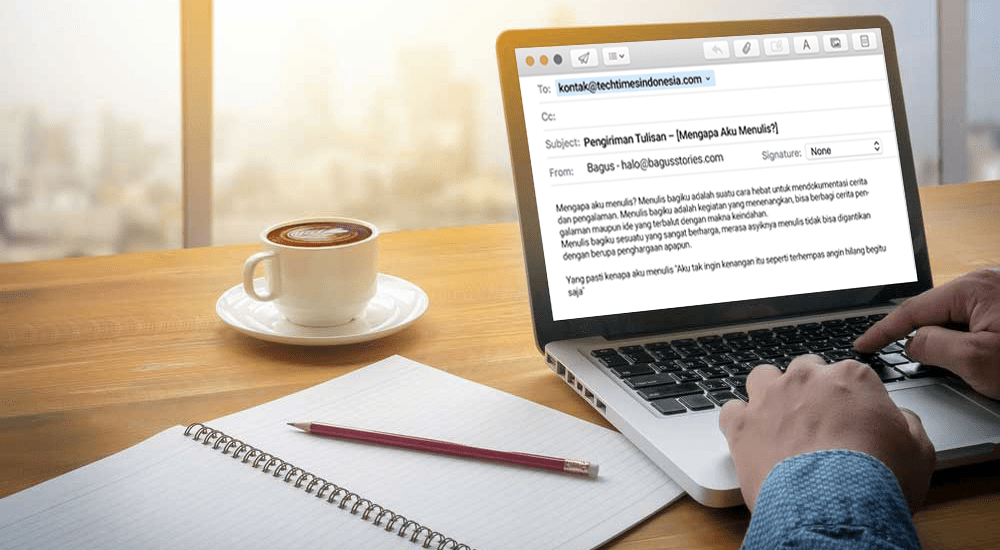Techtimes Indonesia — Dapur adalah ruang yang lebih kompleks daripada yang sering dibayangkan oleh para desainer teknologi.
Ia bukan hanya tempat memasak, tapi juga ruang sosial tempat keluarga berkumpul, tempat cerita diwariskan, dan tempat di mana keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari diambil.
Maka, ketika teknologi mulai menyusup ke dapur dalam wujud kulkas pintar, oven otomatis, hingga alat masak berbasis AI, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan semata “seberapa canggih ini?”, tetapi “untuk siapa teknologi ini bekerja?” dan “nilai-nilai apa yang dibawanya?”
Sejarah dapur selalu terkait erat dengan kerja reproduktif, yaitu jenis kerja yang menopang kehidupan, seperti memasak, membersihkan, dan mengasuh, namun sering kali tak dianggap penting dalam ekonomi formal.
Selama berabad-abad, peran ini dilekatkan pada perempuan. Dalam Caliban and the Witch, Silvia Federici menyatakan bahwa kapitalisme modern dibangun di atas kerja perempuan yang tidak dibayar, terutama di ruang domestik.
Maka, ketika alat-alat dapur modern muncul dengan janji “mempermudah kerja rumah”, kita perlu mempertanyakan: apakah mereka benar-benar membebaskan, atau justru membungkus ketimpangan lama dalam kemasan teknologi terbaru?
Misalnya, mesin pencuci piring atau oven pintar tidak serta-merta menghapus beban mental ibu rumah tangga yang tetap harus memikirkan menu, belanja bahan, dan mengatur jadwal makan.
Teknologi mungkin membuat pekerjaan fisik lebih cepat, tapi tak langsung menyentuh akar persoalan relasi kuasa dalam rumah tangga.
Seperti yang pernah diungkapkan antropolog Lucy Suchman, “Just because something is automated doesn’t mean it’s been thought through.”
Otomatisasi tak selalu berarti kebebasan—apalagi jika yang diotomatisasi justru aspek yang paling manusiawi: perencanaan, perasaan, perhatian.
Dalam banyak kasus, teknologi dapur dikembangkan bukan karena ada kebutuhan nyata dari pengguna, tapi karena pasar membutuhkan inovasi baru untuk dijual.
Kita tidak benar-benar butuh kulkas yang bisa memotret isinya dan mengirimkan gambar ke ponsel. Namun, produsen butuh fitur baru untuk membedakan produk mereka di pasar.
Inilah yang disebut oleh Evgeny Morozov sebagai solutionism, yaitu kecenderungan industri teknologi menciptakan solusi untuk masalah yang sebenarnya tidak ada, atau sengaja dibuat-buat.
Alih-alih merespons kebutuhan nyata, teknologi dapur sering kali justru menciptakan ketergantungan baru.
Masalahnya tidak berhenti di sana. Alat-alat ini, yang tampaknya pintar dan praktis, justru memperluas ruang pengawasan dalam rumah.
Kulkas yang tahu apa yang kita makan, oven yang menyimpan riwayat pemakaian, sensor dapur yang mencatat waktu aktivitas—semua itu memproduksi data yang bisa diakses, dianalisis, bahkan dijual.
Maka, teknologi dapur hari ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal privasi digital, kontrol, dan kapitalisasi kehidupan domestik.
Kita butuh cara berpikir lain tentang teknologi. Bukan sebagai sekadar alat yang netral, tapi sebagai cerminan nilai, hubungan sosial, dan visi tentang kehidupan yang diinginkan.
Dalam Tools for Conviviality, Ivan Illich menyatakan bahwa teknologi yang sehat adalah yang memungkinkan orang bertindak dengan otonomi, saling mendukung, dan menjalin relasi yang bermakna.
Maka, dapur yang sehat bukan yang dipenuhi alat otomatis, melainkan dapur yang mengundang kerja sama: tempat anak-anak belajar memasak bersama orang tuanya, tempat keluarga menyusun menu bersama, tempat makanan disiapkan dengan cinta—bukan hanya efisiensi.
Bayangkan, alih-alih alat masak yang serba otomatis, kita punya perangkat yang bisa mendorong kesadaran ekologis.
Kompor yang memberi notifikasi jejak karbon tiap bahan yang dimasak, atau tempat sampah dapur yang secara visual menunjukkan berapa banyak sisa makanan yang dibuang dalam seminggu.
Teknologi ini bukan untuk menggantikan kerja manusia, tapi untuk mengajak berpikir lebih bijak dan lebih dalam.
Di Indonesia, masih banyak dapur yang tidak tersentuh oleh teknologi canggih. Dapur dengan pawon tradisional, tungku kayu, alat-alat manual.
Kita sering menganggap dapur seperti ini sebagai “ketinggalan zaman”, padahal dalam banyak hal, mereka justru lebih berdaulat: bisa mengolah bahan lokal, tidak tergantung listrik, menghasilkan limbah yang minim.
Dapur tradisional adalah ruang hidup yang organik, penuh cerita dan kebijaksanaan.
Kita perlu lebih banyak belajar dari sana, bukan sekadar menggantinya dengan gadget baru.
Teknologi seharusnya tidak mengendalikan manusia, tetapi mendukung manusia untuk hidup lebih bermakna.
Dapur adalah tempat emosi bertemu dengan fungsi, tempat ritual keseharian bertemu dengan kreativitas.
Maka, teknologi yang ditempatkan di dapur harus mampu menghargai dimensi ini.
Kita tidak butuh alat pintar yang hanya menambahkan fitur, tapi alat yang bisa memperdalam relasi: antara manusia dan makanan, antara generasi, antara ingatan dan harapan.
Manifesto ini bukan ajakan untuk anti-teknologi, tapi ajakan untuk berpikir lebih etis dan manusiawi.
Kita ingin teknologi yang benar-benar bekerja untuk kita, bukan membuat kita bekerja untuknya. Kita ingin dapur yang memanusiakan, bukan mendisiplinkan.
Kita ingin alat yang menambah cerita, bukan menghapus jejak.
Karena pada akhirnya, teknologi dapur yang ideal bukanlah soal seberapa cepat kita bisa menyelesaikan masak, tapi seberapa banyak kehidupan yang bisa kita rayakan di dalamnya.