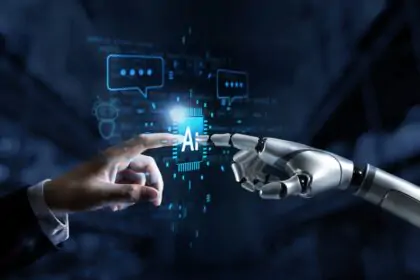Za, hari ini aku kembali melewati aspal hitam Serang—Labuan. Tapi kali ini ada yang berbeda. Tidak ada kamu di sampingku. Entah mengapa aku begitu kesepian. Aku didera rasa kehilangan yang amat sangat.
Kamu tahu, Za? Ketika bus melintasi pertigaan Panimbang, seketika ingatanku menyeret ke masa tiga bulan yang lalu. Saat itu kita di pantai Anyer.
Dalam suasana kemuning yang bertahta, diselingi irama deburan ombak, aku meraih tanganmu. Lalu aku labuhkan sebuah kecupan di sana. Kecupan pertamaku untuk seorang perempuan. Jujur, Za, itu adalah pengalaman pertamaku mengungkapkan gejolak kagum pada seorang hawa. Pernah beberapa kali aku merasakan hal yang namanya jatuh cinta. Namun selalu kalah—terlambat, atau bertepuk sebelah tangan. Dua alasan yang membuat aku sempat lupa apa definisi cinta yang sebenarnya. Tapi ketika bertemu matamu itu, aku kembali merasakan perasaan yang sama ketika pertama kali aku mengagumi wanita. Ah, bukan! Aku bukan sekadar jatuh cinta. Ini adalah rasa dari sebuah ramuan yang aku sendiri tidak tahu namanya apa. Ini lebih dari sekadar mengagumi, rasa ingin memiliki. Rasa ini begitu tulus ingin bersamamu.
“Aku suka kamu,” kata-kata klasik itu berlompatan tanpa mampu aku bendung. Begitu bulat, bagai bulan empat belas.
Kamu menatapku sejenak, lalu membuang pandangan ke laut lepas. Diam seribu kata.
“Maaf, kalau pengakuanku ini membuatmu malu,” tiba-tiba aku didera perasaan menyesal telah membuatmu tercenung murung. Aku melepaskan tanganmu yang sedari tadi berada dalam genggamanku. Kamu tersentak, lalu kembali menatapku, lalu menunduk.
Aku tidak berani merusak hening yang kamu ciptakan. Tak ada satu kata pun yang berani berlompatan. Ah, apalah arti kata-kata kalau hati sudah bicara. Bukankah begitu, Za?
Anyer semakin rapuh sore itu. Di atas kita, Tuhan mulai melukis langit dengan warna keemasan yang begitu eksotis. Dari kejauhan camar-camar terbang membelah angkasa dan menyibak lautan. Sementara diam masih menguasai antara aku dan kamu.
“Ri, kita pulang, yuk! Sudah sore,” akhirnya kebekuan itu cair.
Aku mengembuskan napas panjang, “yuk, aku antar kamu, ya.”
Kita meninggalkan Anyer dalam suasana petang yang membayang. Sebelum malam jatuh ke pelukan pekat dan senja bersalin rupa menjadi malam, aku harus segera mengantarmu pulang. Ke Labuan.
Keesokan harinya kita membuat janji ketemuan di Mall of Serang. Aku menyanggupi. Satu alasan yang kuat adalah kamu pasti akan memberikan jawaban atas pengakuanku kemarin sore. Aku tata perasaanku serapi mungkin. Detak jantung tak beraturan, lalu pipi yang bersemu kemerahan. Bah, sungguh tak biasa, Za. Baru kali ini merasakan perasaan aneh macam ini.
Kamu memilih tempat di pojok. Seperti kebiasaanmu saat memilih tempat duduk di bus. Kamu menyandarkan kepalamu ke dinding kaca, membiarkan ujung jilbabmu terurai. Sementara di bawah kita terhampar pemandangan Kota Serang yang makin hari makin apik saja. Pesanan makanan kita datang. Ayam bakar dan es jeruk. Andai saja di sini ada otak-otak atau sate bandeng, aku ingin memesan itu saja. Tapi itu mana mungkin ada, kamu bersikeras ingin ke MoS saat aku tawarkan pertemuan kita di tempat biasa. Jalan Fatah Hasan, di dekat Bunderan Ciceri. Tapi kamu katakan ingin ke MoS. Aku pun mengalah.
“Ri, aku makin cinta dengan Serang,” kamu bersuara.
“Oh ya, aku juga,” jawabku sembari menyeruput es jeruk. Hawa segar mengalir di tenggorokanku.
“Kota Serang makin hari makin cantik saja, ya, Za.” Kali ini aku yang bersuara. Melengok ke barisan kendaraan yang menuju arah tol Serang Timur.
“Aku suka pemandangan di hadapan kita, Ri. Coba kamu lihat mobil-mobil itu, lalu masjid di samping Sari Asih. Kita seperti berada di Dubai, ya.”
“Hahaha,” aku memecah tawa. Membenarkan analogimu. “Jadi ini alasan kamu mengajak kita ketemuan di MoS, aku baru tahu alasannya.”
“Bukan hanya itu, Ri. Ada yang lebih dari sekadar menikmati suasana Serang dari MoS,” kamu membuatku diserbu tanya tanya.
“Maksud kamu?”
Kamu menyeruput es jeruk di hadapanmu. Lalu meneguknya pelan. Caramu meneguk sungguh anggun, Za. Lagi-lagi aku menemukan sisi keanggunan yang lain di gadis Banten, seperti kamu.
“Aku minta maaf tidak menjawab pertanyaanmu kemarin sore.”
“Pertanyaan yang mana?” aku pura-pura lupa.
Kamu menatap ke arahku. Tajam dan penuh makna. Oke, aku mengaku. Pernyataanku yang kamu anggap menjadi pertanyaan bagimu. Mungkin itu lebih tepat.
“Aku tidak menuntut jawaban kamu, Za. Bagiku kebersamaan kita jauh lebih penting. Terlepas dari status pacaran, aku harap kita masih berteman,” bibirku meniru bisikan darah pada jantung.
“Justru itu, Ri. Mungkin, terkadang aku seperti tak bisa menjawab pertanyaanmu. Atau sekadar membalas pernyataan-pernyataanmu yang bagiku terdengar begitu sempurna.
Aku menatapmu serius. Ada bagian sensitif di hatiku yang kamu sentil. Begitu pas, membuatnya merah meradang.
“Maksudmu aku gombal? Aku memang seorang penulis yang biasa meramu kata. Tapi kata-kata yang terlontar ketika bersamamu sungguh tak pernah aku siapkan sebelumnya, Za. Sama ketika aku mencuri ide dari semesta. Refleks begitu saja. Mencintaimu adalah sebuah ide luar biasa yang diberikan Tuhan padaku. Lalu mengalir tanpa skenario atau kerangka apa pun. Aku bukan tipe penulis yang punya pretensi dalam melahirkan cerpen-cerpenku, Za. Aku menuliskan apa yang rasa, apa yang aku alami. Itu saja.”
Kamu termenung lama mendengarkan penjelasanku yang membabi buta. Oh, maafkan aku, Za. Aku terlalu takut kamu cap sebagai pengarang yang pandai merayu. Memanfaatkan kebisaanku untuk menaklukkan kamu. Sungguh, Za. Aku tak pernah bermain-main dengan kata-kata ketika berhadapan dengan kamu. Puisi-puisi itu, cerpen, atau buku yang aku berikan itu. Itu nyata aku alami.
Mata cokelatmu mengamati mukaku. Aku paham siratan mata itu. Siratan yang kaget mendengar aku bereaksi secepat ini. Itu yang aku tafsirkan, kamu mengira aku tidak terima dicap sebagai pengarang gombal yang suka memanfaatkan kata merayu wanita. Sungguh, Za. Aku hanya takut statusku sebagai penulis kamu jadikan alasan bahwa aku berpura-pura.
Kamu masih diam, masih menatapku. Lama. Aku kelabakan. Bertanya-tanya dalam perasaan cemas. Tanya itu mendirikan dinasti di kepalaku, mendirikan benteng yang penasaran yang kokoh.
“Besok aku akan pergi,” kalimatmu singkat, namun begitu mampu membuatku tersedak.
“Pergi? Ke mana?” aku memburumu dengan tanya.
Kamu menghela napas dalam. Lalu membuangnya dengan cara yang lagi-lagi anggun.
“Hariri….” kamu menyebut namaku, menggantung.
Tatapan kita bertaut, mengalirkan segala rasa keingintahuanku, rasa penasaranku akan kalimatmu yang mengandung misteri, Za.
“Kamu masih ingat, kan? Dulu aku pernah bilang kalau mata kita sama, sama-sama mencintai suasana sore dan sesak di bus Murni Jaya. Kamu tahu itu artinya apa?” kamu justru membuat aku makin berranya-tanya. Aku menggeleng.
“Itu artinya, kita juga mempunyai hati yang sama. Aku juga sayang kamu, Ri….”
Oh, aku sungguh berada dalam rasa yang berbunga-bunga. Refleks tanganku merebut tanganmu. Menggenganmya. Aku ingin kamu tahu seperti apa hebatnya getaran rasa aneh yang tiba-tiba menguasaiku, Za. Tapi aku dibuat kaget ketika kamu buru-buru melepaskan genggamanku.
“Sttt…” ujung telunjukmu mendarat di bibirku. Aroma wangi menguar. Aku menghirupnya pelan.
“Tapi aku akan pergi. Jalan kita masih panjang, Ri. Aku percaya, kamu pasti paham maksudku. Aku kenal kamu….”
Kalimatmu seperti tamparan hebat. Membuatku tersadar bahwa keadaan akan berubah seratus delapan puluh derajat. Kamu katakan kalau kamu kan melanjutkan S2 di Prancis. Saranku padamu untuk sama-sama di kuliah di Serang tidak kamu hiraukan. Aku coba menawarkan Bandung, lagi-lagi kamu membuatku mengalah, Za. Baiklah, aku mengalah. Tapi haruskah aku mengalah juga ketika kamu menolak untuk menginap di Serang untuk malam ini saja? Aku rasa ibu kostanmu masih memaklumi, walaupun hari ini urusan kuliah dan segala embel-embelnya sudah kamu selesaikan. Ah, tepatnya aku bukan mengalah, tapi aku marah, Za. Aku ingin tahu reaksimu ketika aku ngambek.